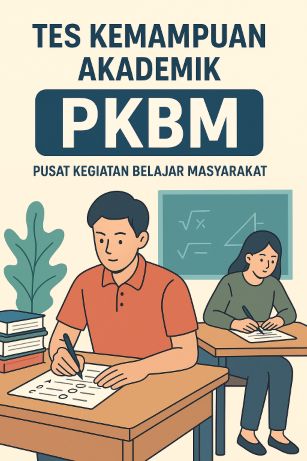Ketika Pendidikan Kehilangan Jiwa: Dari Bencana TKA, Martabat Guru, hingga Kegagalan Menuntun Kodrat Manusia
Budiawan | 25 Desember 2025
Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 seharusnya tidak lagi dibaca sebagai statistik pendidikan. Ia lebih pantas dibaca sebagai diagnosis kebudayaan. Angkanya telanjang dan memalukan: mayoritas siswa SMA Indonesia gagal menunjukkan kemampuan dasar yang selama puluhan tahun kita anggap remeh—berhitung sederhana, berbahasa Indonesia secara runtut, dan berbahasa Inggris secara fungsional. Ini bukan soal “rendah”. Ini ambruk.
Ketika murid kelas akhir SMA nyaris tak mampu membaca wacana dengan utuh dan bernalar numerik secara dasar, maka yang runtuh bukan hanya sekolah, melainkan fondasi republik pengetahuan. Lebih mengganggu lagi, bencana ini datang justru di tengah gegap gempita jargon reformasi, inovasi, dan merdeka belajar.
Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: apa yang sebenarnya sedang kita bangun dalam pendidikan Indonesia?
Pendidikan Tanpa Jiwa: Akar Masalah yang Tak Pernah Dibicarakan
Ki Hajar Dewantara sejak awal meletakkan pendidikan sebagai proses menuntun hidup, bukan sekadar mengisi kepala. Pendidikan, bagi Ki Hajar, adalah kerja peradaban yang menyentuh jiwa, hati, dan akal manusia—dalam urutan yang jelas.
Namun sistem pendidikan kita hari ini berjalan terbalik. Kurikulum, asesmen, dan kebijakan publik sibuk mengejar output kognitif sambil mengabaikan ketahanan batin peserta didik dan pendidik. Kita memproduksi silabus, modul, platform, dan dashboard—tetapi lupa menyiapkan manusia yang sanggup bertahan di dalamnya.
TKA 2025 memperlihatkan akibatnya secara brutal. Ketika tekanan administratif meningkat, guru dibiarkan berjalan sendirian di ruang kelas yang penuh tuntutan tetapi miskin perlindungan. Murid dipacu untuk “mandiri”, tetapi tanpa fondasi jiwa yang cukup untuk menanggung beban belajar yang tercerai-berai.
Dalam bahasa Ki Hajar: anak dituntut berlari, sementara tanah tempat berpijaknya rapuh.
Kurikulum Merdeka: Merdeka dari Arah, Merdeka dari Tanggung Jawab
Kurikulum Merdeka datang dengan niat baik, tetapi dijalankan dengan logika teknokratis yang miskin antropologi pendidikan. Fleksibilitas dijadikan mantra, sementara arah dibiarkan kabur. Guru diminta kreatif, tetapi dipagari administrasi. Murid diminta eksploratif, tetapi kehilangan struktur dasar.
Hasilnya adalah paradoks: kurikulum yang katanya membebaskan justru melahirkan kecemasan kolektif—di ruang guru, di kepala murid, dan di rumah orang tua. Tanpa fondasi jiwa dan hati, kebebasan berubah menjadi beban.
Ki Hajar Dewantara tidak pernah membayangkan kemerdekaan belajar sebagai pelepasan tanggung jawab negara. Sebaliknya, kemerdekaan justru menuntut kehadiran negara yang lebih dewasa: melindungi guru, menjaga arah, dan memastikan proses pendidikan tetap manusiawi.
Di sinilah relevansi Perda Perlindungan Guru—seperti yang dilakukan Pemkot Bogor—menjadi penting. Perlindungan bukan sekadar hukum, melainkan pengakuan bahwa pendidikan adalah kerja batin, bukan sekadar pekerjaan administratif.
Jiwa yang Rapuh, Hati yang Lelah, Otak yang Dipaksa Bekerja Sendiri
TKA 2025 juga mengungkap sesuatu yang lebih sunyi: kelelahan eksistensial dalam pendidikan kita. Murid kehilangan daya tahan belajar. Guru kehilangan makna mengajar. Sekolah kehilangan orientasi mendidik.
Dalam kerangka Ki Hajar, ini terjadi karena jiwa tidak lagi dijadikan fondasi. Jiwa adalah kemampuan bertahan dalam proses panjang dan sering tidak adil. Tanpa jiwa yang kuat, hati cepat letih. Tanpa hati yang hidup, relasi guru–murid membeku. Dan ketika itu terjadi, otak—sekeras apa pun dipaksa—tak lagi bekerja optimal.
Kita boleh menambah jam pelajaran, mengganti asesmen, atau memperbarui platform. Tetapi tanpa menata ulang urutan ini—jiwa, hati, baru akal—semua itu hanya kosmetik kebijakan.
Negara, Kekuasaan, dan Ilusi Reformasi
Di sinilah kritik paling tidak nyaman perlu disampaikan: pendidikan telah direduksi menjadi proyek kekuasaan yang ingin tampak progresif, bukan proses kebudayaan yang mau bersabar. Negara terlalu sibuk terlihat modern, tetapi lupa mendengar denyut ruang kelas.
Kekuasaan senang pada kebijakan yang cepat dipresentasikan, tetapi enggan pada kerja sunyi membangun ketangguhan manusia. Padahal pendidikan bukan lomba inovasi, melainkan kesetiaan panjang pada proses menumbuhkan manusia.
Ki Hajar Dewantara mengingatkan: pendidikan adalah laku kebudayaan, bukan sekadar urusan kementerian. Ketika negara gagal memahami ini, maka yang lahir bukan generasi merdeka, melainkan generasi bingung yang dipaksa optimis.
Penutup: Tamparan yang Perlu Didengar
Hasil TKA 2025 bukan kegagalan murid. Ia adalah cermin kegagalan kolektif kita—sebagai negara, sebagai pembuat kebijakan, sebagai masyarakat yang terlalu lama memuja kepintaran dan lupa menumbuhkan ketangguhan.
Jika pendidikan terus dijalankan tanpa jiwa, tanpa hati, dan hanya mengandalkan otak, maka jangan kaget bila angka-angka terus memburuk sementara jargon terus diproduksi.
Karena bangsa ini tidak runtuh karena kurang pintar, melainkan karena terlalu lama membiarkan pendidikan kehilangan jiwanya—dengan sadar, oleh kekuasaan, dan atas nama kemajuan.
—
Referensi
- Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka
- Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning
- Daniel Goleman, Emotional Intelligence; Primal Leadership
- Brené Brown, Dare to Lead
- Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership
- Amy Edmondson, The Fearless Organization
- World Economic Forum, Future of Jobs Report
- Artikel Dr. Kholid Harras, Inharmonia.id (2025)